Kedudukan As-Sunnah dan Keterkaitannya Dengan Al-Qur’an
Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal
Syarah: Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali
www.ilmusunnah.com
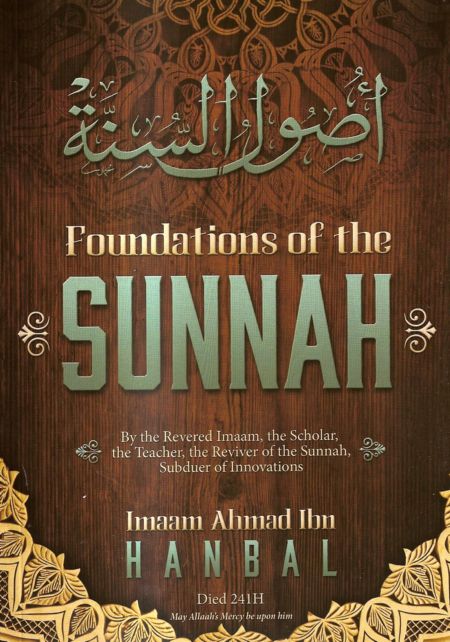
وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ، وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ، إِنَّمَا هِيَ الِاتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَى
“Dan As-Sunnah di sisi kami adalah atsar (setiap petunjuk yang diriwayatkan daripada) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan As-Sunnah itu, ia menafsirkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk yang menjelaskan kandungan Al-Qur’an. Dan tidak ada dalam As-Sunnah ini qiyas. Tidak dipertentangkan dengannya permisalan-permisalan, dan tidak-lah As-Sunnah itu diambil (atau dicapai) dengan semata-mata akal, dan tidak pula dengan hawa nafsu. Tetapi hendaklah ia diterima dengan cara al-ittiba’ (mengikuti Rasulullah) dan dengan meninggalkan hawa nafsu.” (lihat: Ushulus Sunnah Imam Ahmad)
Syarah dan huraian oleh Syaikh Rabi’:
Beliau (Imam Ahmad bin Hanbal) rahimahullah mengatakan:
“As-Sunnah di sisi kami adalah atsar (setiap petunjuk yang diriwayatkan daripada) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.”
Apa itu As-Sunnah? Beliau katakan, “Atsar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.” Yakni semua ucapan, perbuatan, dan taqrir (persetujuan) beliau Shallallhu ‘alaihi wa Sallam.
Di sisi kita ada Al-Kitab dan ada pula As-Sunnah. Lalu apa itu As-Sunnah? As-Sunnah ialah atsar (jalan hidup) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Iaitu segala ucapan, perbuatan, serta sikap persetujuan beliau. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta’ala wajibkan atas kita untuk mengikutinya serta berpegang teguh dengannya.
Lalu penulis pun mula menjelaskan tentang kedudukan As-Sunnah serta keterkaitannya dengan Al-Qur’an:
“Dan As-Sunnah itu, ia menafsirkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk yang menjelaskan kandungan Al-Qur’an.”
Demikianlah As-Sunnah, ia menjelaskan Al-Qur’an.
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar engkau menerangkan kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka itu.” (Surah An-Nahl, 16: 44)
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
“Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul..” (Surah An-Nisaa’, 4: 59)
Makna “kembalilah kepada Allah”, adalah kepada Kitabullah (Al-Qur’an). Dan makna “kembalilah kepada Rasul”, adalah dengan merujuk (langsung) kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam di masa hidupnya, dan kepada sunnah beliau setelah wafatnya Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Jadi, As-Sunnah merupakan tempat kembalinya (urusan) manusia dan sumber rujukan mereka. As-Sunnah dan Al-Qur’an berada pada kedudukan yang sama; sebagai hujjah pendalilan dalam bab-bab ‘aqidah, hukum halal-haram dan semua bidang agama yang lainnya. As-Sunnah merupakan rujukan utama sebagaimana Al-Qur’an.
Oleh kerana itu kita dapati para salaf terdahulu, jika datang sebuah pertanyaan kepada mereka, sama ada dalam masalah ‘aqidah atau selainnya, maka mereka menjawabnya dengan apa yang terbetik dalam benak mereka dari nash Al-Qur’an mahupun sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, dan tiada beza antara keduanya. Akan datang contoh perihal ini dari sikap ‘Umar, Abu Bakr, Ibnu ‘Umar, ataupun sahabat lainnya radhiyallahu ‘anhum.
(Perkataan Imam Ahmad), “(As-Sunnah) sebagai petunjuk yang menjelaskan kandungan Al-Qur’an.”
As-Sunnah menjelaskan dan merinci yang global (mujmal), menerangkan yang samar (mubham), mengaitkan yang lepas tidak diikat (muthlaq), serta mengkhususkan yang masih bersifat umum. As-Sunnah menjelaskan kepada kita (contohnya) perkara-perkara solat, sama ada yang berkaitan waktunya, jumlah (raka’at)nya, mahupun perincian-perinciannya serta apa-apa yang perlu kita baca di dalamnya. Apa yang kita ucapkan ketika ruku’, apa pula yang kita ucapkan ketika sujud. Ini semua masuk dalam kerangka “As-Sunnah.” Ketika Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
“Tegakkanlah solat dan tunaikanlah zakat.”
Dan ini Allah Subhanahu wa Ta’ala sering sebutkan (dalam Al-Qur’an), maka hanya As-Sunnah yang menjelaskan serta merinci perkara tersebut. Oleh kerana itu, As-Sunnah merupakan petunjuk yang menjelaskan, iaitu penjelas serta penerang terhadap (isi) Al-Qur’an yang masih global. As-Sunnah juga mengkhususkan lafaz-lafaz yang umum, dan mengaitkan bentuk-bentuk yang muthlaq. Jadi As-Sunnah adalah “pentafsir Al-Qur’an” sebagaimana telah disebutkan Imam Ahmad rahimahullah, sekaligus juga sebagai “petunjuk yang menjelaskan Al-Qur’an”, sebagaimana beliau rahimahullah katakan.
وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ
“Dan tidak ada dalam As-Sunnah ini qiyas.”
Maknanya tidak ada qiyas dalam agama Allah Subhanahu wa Ta’ala. Apabila telah datang “sungai” Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka batallah “sungai” akal. Jika datang nash, maka batallah qiyas. Jadi, dalil tidak boleh dipertentangkan dengan akal, fikiran, analogi, atau apapun juga. Tidaklah ada kelonggaran bagi kita melainkan dengan hanya tunduk menerima (dalil tersebut – pent.).
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan,lalu mereka tidak mendapati keberatan dalam jiwa-jiwa mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan tasliim (tunduk dan patuh).” (Surah An-Nisaa’, 4: 65)
Sebahagian orang ada yang berlebihan dalam menggunakan qiyas, sampai pada tingkatan (berani) menolak dalil yang datang dengan qiyas tersebut. Dia mengatakan:
“Nash ini telah menyelisihi kaidah ushul. Nash ini telah menyelisihi qiyas.”
Demikianlah, mereka berlebihan dalam qiyas. Oleh kerana itu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan bantahan ini terhadap mereka.
Sekalipun terkadang didapati adanya qiyas-aula, akan tetapi itu hanyalah sebagaimana dikatakan: “umapama bangkai,” yang hanya boleh dimakan pada saat keadaan darurat saja.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab kecilnya yang berjudul, “Ma’arijul Wushul ila Bayani anna Ushul Ad-Din wa Furu’ihi Qad Bayyanaha Ar-Rasul” (Tangga Yang Menghantarkan Kepada Penjelasan bahawa Pokok-pokok Dasar Agama dan Cabang-cabangnya Telah Dijelaskan oleh para Rasul), beliau berkata:
“Dari penelitian, tidaklah ada satu ijma’ pun, kecuali pasti kami dapati padanya nash (dalil).”
Demikian pula, tidak ada suatu golongan yang mengkiaskan suatu perkara, kecuali pasti ditemukan padanya nash yang semakna dengan qiyas tersebut. Hanya cuma manusia berbeza-beza tingkatannya dalam memahami mahupun pendekatan berbagai nash yang ada. Sangat jarang di antara mereka yang dapat menyerap ataupun mendekatkan nash-nash tersebut semisal Al-Imam Ahmad rahimahullah. Oleh kerana itu, engkau dapat menemukan qiyas yang sahih di sisi kebanyakan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala sentiasa memberi petunjuk buat mereka kepada qiyas sahih. Akan tetapi seandainya diperluas pengajian dan penelitian terhadap As-Sunnah, tentu akan didapati bahawa di sana telah ada nash dari Pembuat syari’at (Allah). Kerana, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah menjelaskan semua ushul (dasar-dasar) agama serta furu’ (cabang-cabang)nya tanpa membiarkan begitu saja sesuatu apapun.
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
“Tidaklah kami lalaikan sesuatupun dalam Al-Kitab.” (Surah Al-An’am, 6: 38)
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah Aku cukupkan atas kalian nikmat-Ku, dan telah Aku redhai Islam sebagai agama bagi kalian.” (Surah Al-Ma’idah, 5: 3)
Jadi, agama kita telah sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Ada sebahagian orang ber-ijtihad dengan menggunakan qiyas, dan ternyata qiyasnya sahih, termasuk qiyas yang bersesuaian dengan nash. Dia telah mengumpulkan sekian banyak ‘illah yang teranggap. Akan tetapi dalam permasalahan tersebut terdapat nash yang belum sampai kepadanya, seandainya nash tersebut sampai kepadanya, maka tentunya ia akan berhujjah dengannya dan meninggalkan qiyasnya.
Setelah itu datang orang setelahnya. Dia banyak mempelajari As-Sunnah dari kitab-kitab jami’, musnad, mu’jam (yakni dalam bidang hadis) dan seterusnya hingga akhirnya mendapatkannya. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah misalnya, beliau dapati bahawa ternyata dalam suatu ijma’ (kesepakatan ulama) terdapat nash. Jadi, para ulama sebelumnya telah bersepakat dengan ijma’ yang sahih, sesuai dengan dalil-dalil (nash) syar’i. Dan seandainya mereka mendapati nash dalam permasalahan tersebut, tentu mereka akan berdalil dengannya. Namun tidak mereka jumpai. Lalu datang para ulama setelahnya, seperti Ibnu Taimiyah dan selainnya yang meneliti, hingga mendapati adanya ijma’ dalam suatu permasalahan, yang sebenarnya sudah ada dalilnya yang kuat dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tentang itu.
Jadi di sana ada qiyas-qiyas yang dipakai para ulama, yakni qiyas yang sahih. Namun di sisi lain, ada pula nash-nash dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang belum sampai pada pengetahuan mereka.
Bagaimanapun keadaannya, Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah orang yang tegas dalam membantah qiyas. Beliau mengingkari banyak perkara yang didakwa sebagai ijma’. Ketika ada yang mengatakan, “Permasalah ini telah disepakati oleh para ulama”, maka beliau ingkari dengan mengatakan, “Tahukah engkau bahawa padanya ada khilaf (perselisihan pendapat)?!”
Kerana itu, hendaknya dia katakan, “Saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam permasalahan ini.” Dan janganlah dia terburu-buru mengatakan, “Umat ini telah sepakat dalam masalah ini.” Yang lebih selamat, hendaklah dia katakan, “Aku tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini.” Kerana, mungkin saja akan ditemui adanya khilaf dalam permasalahan tersebut, tetapi itu belum sampai kepadanya atau bahkan belum dia teliti (dengan sedalamnya).
Kemudian penulis (Imam Ahmad) berkata:
“…Tidak dipertentangkan dengannya permisalan-permisalan.” Apabila datang kepadamu sebuah nash, maka terimalah dengan pasrah.
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak mendapati suatu keberatan dalam jiwa-jiwa mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Surah An-Nisaa’, 4: 65)
Jika ada seseorang yang membawakan kepadamu sebuah nash yang kuat lagi sahih ataupun hasan, maka jangan (sekali-kali) kau katakan, “Demi Allah, demi Allah…”, yakni kau pertentangkan dengan permisalan (atau andaian-andaian) yang lainnya.
Perkara seperti ini pernah dipesankan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah Ibnu Majah rahimahullah, iaitu ketika beliau mengatakan:
“Sesiapa yang memakan hidangan yang tersentuh api (yakni yang telah dimasak dengan api – pent.), maka hendaklah dia berwudhu.” (lihat: Sunan Ibnu Majah, no. 22, 485. Sunan At-Tirmidzi, no. 79)
Setelah beliau meriwayatkan hadis yang memerintahkan berwudhu’ dari makanan yang tersentuh api ini, salah seorang sahabat berkata kepada beliau:
“Adakah menurut engkau (wudhu’) kerana benda panas, adakah aku juga perlu berwudhu’ (lagi) dengan sebab itu?!”
Maka beliau jawab:
يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ
“Wahai anak saudaraku, jika telah sampai kepada engkau hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, janganlah engkau pertentangkan dengan membuat permisalan-permisalan (atau andaian-andaian).”
Yakni maksudnya, terimalah. Ini adalah sebuah kaedah, baarakallaahufiikum.
Penulis mengatakan:
“dan tidak-lah As-Sunnah itu diambil (atau dicapai) dengan semata-mata akal, dan tidak pula dengan hawa nafsu.”
Yakni maksudnya, bahawa As-Sunnah itu tidak akan dicapai dengan semata akal-akal kita. Tidak pula dengan pelbagai hawa nafsu. Ia (As-Sunnah) hanya dicapai dengan penukilan (riwayat dalil).
Jika engkau menghendaki As-Sunnah dan petunjuk, carilah ilmu dan belajarlah. Jika As-Sunnah datang kepadamu, fahamilah kandungannya. Gunakanlah akalmu (yang benar) dalam memahaminya.
مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
“Sesiapa yang Allah kehendakinya dengan kebaikan, nescaya Allah akan memahamkannya dalam (perkara) agama.” (Shahih Al-Bukhari, no.71. Muslim, no. 1037)
Adapun jika tanpa berpandukan dalil yang benar, tanpa sunnah satu pun padanya, lalu engkau berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka ini termasuk berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu.
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
“Katakanlah, “Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji yang nampak mahupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan hujjah untuk itu serta berbicara atas nama Allah pada apa-apa yang tidak kalian ketahui.” (Surah Al-A’raaf, 7: 33)
Sebab itu, seorang muslim diwajibkan untuk berhenti di hadapan dalil, sama ada itu dalam perkara-perkara ‘aqidah, ibadah, mahupun dalam masalah halal-haram. Adapun dalam perkara duniawi, maka silakan berijtihad.
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ
“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” (Shahih Muslim, no. 2363)
Sedangkan hukum asal dalam perkara agama adalah haram, kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang membuat syari’at. Sebab itu, jika engkau berkata-kata dalam agama Allah Subhanahu wa Ta’ala hanya dengan akalmu, bermakna engkau telah mengikuti hawa nafsumu, dan mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa Ta’ala tanpa ilmu. Dan ini termasuk dari dosa terbesar; bahkan pada beberapa keadaan boleh sampai kepada tingkatan yang lebih besar dari kesyirikan, sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah.
Beliau pernah menjelaskan ayat di atas dan berkata:
“Sesungguhnya nash ini bertingkat-tingkat, dimulai dari dosa yang terendah hingga yang tertinggi. Maka yang terbesar adalah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ia lebih besar dari syirik , kerana telah masuk di dalamnya kesyirikan itu sendiri dan selainnya. Bahkan, tidaklah syirik itu muncul melainkan dari ucapan-ucapan pengikut kebathilan dan para pengikut kesesatan.”
Oleh kerana itu, waspada dan berhati-hatilah dari berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan mengikuti hawa nafsu, akibat terpedaya dengan (kehebatan) akal, kecerdasan dan pemahaman.
Kefaqihan seseorang dalam nash (dalil) tadi, sebagaimana sikap para sahabat dan tabi’in, juga seperti yang dikatakan penulis di sini:
“…Tetapi hendaklah ia diterima dengan cara al-ittiba’ (mengikuti Rasulullah) dan dengan meninggalkan hawa nafsu.”
Maknanya, tidak ada kekuasaan akal ataupun kebebasan hawa nafsu terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta’ala. Agama ini hanya dengan meneladani Rasul (ittiba’), meninggalkan hawa nafsu, dan memurnikan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rabb semesta alam.
Rujukan: Syarah Ushulus Sunnah, m/s. 9-12. Edisi pdf: http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=5&id=201




